Gus Dhofir: Ilmu Tak Lagi Diutamakan
Jum'at, 09 Januari 2026 - 17:16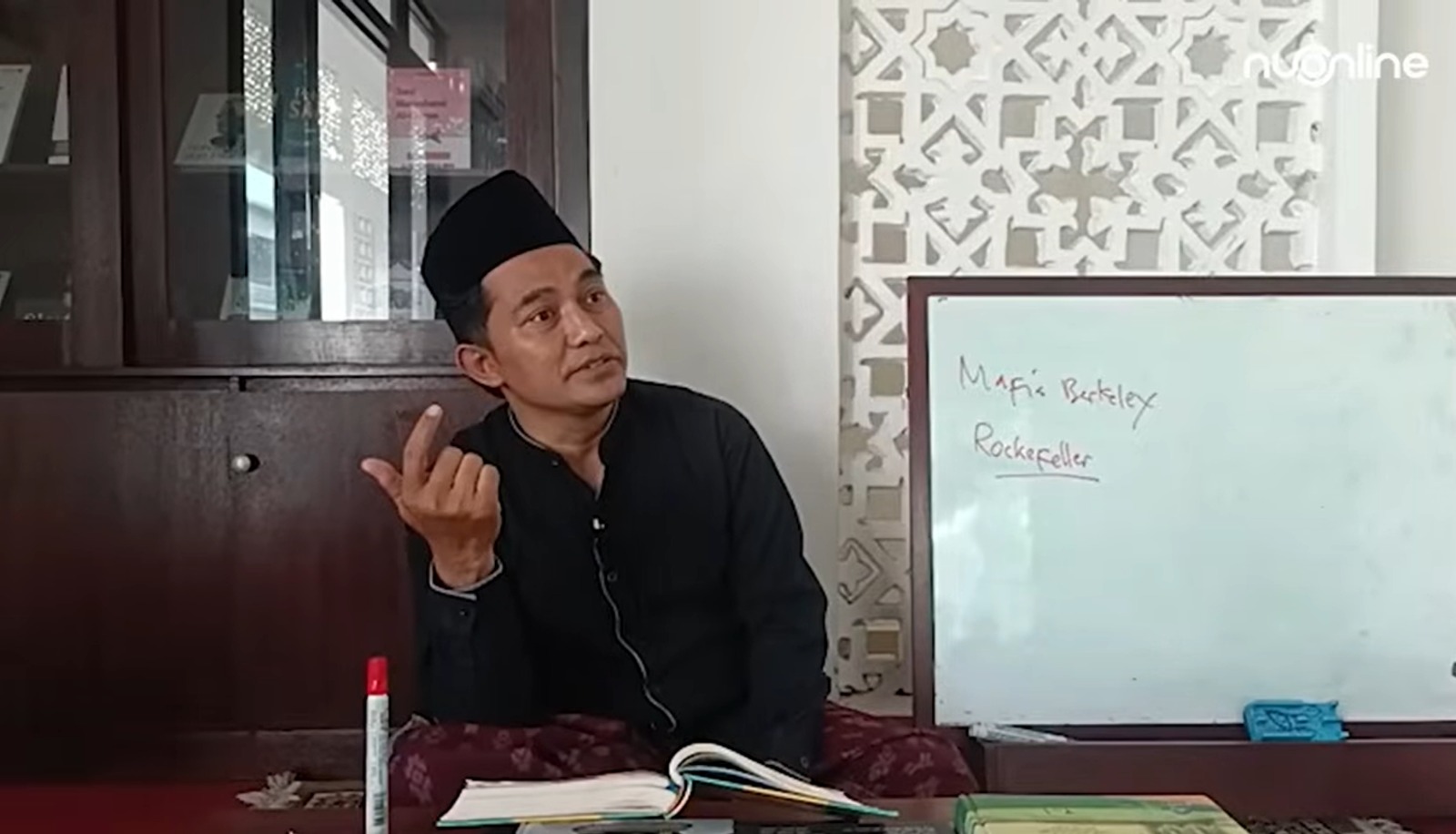
alfikr.id, Probolinggo- “Setiap Anda
belajar, setiap bertemu teman baru atau santri baru, pasti yang ditanyakan
adalah kalau lulus dari sana jadi apa? Dapat kerja apa? Pasti pertanyaannya
begitu, ya,” ucap Achmad Dhofir Zuhry, atau sering disapa Gus Dhofir, saat
kajian Tafsir Tematik di Pesantren Luhur Baitul Hikmah, Malang, Kamis
(25/12/25).
Menurut Gus
Dhofir, kesadaran semacam itu telah lama menggerogoti orientasi pendidikan di
Indonesia. Sekolah akhirnya dipahami semata-mata sebagai sarana untuk
mendapatkan pekerjaan, baik oleh peserta didik maupun oleh para wali murid.
“Akibatnya,
proses pendidikan diarahkan pada kepentingan pasar kerja, bukan pada
pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri,” katanya.
Sekolah favorit
menjadi dambaan para wali murid, kata Gus Dhofir, anak-anak disekolahkan di
lembaga tertentu, bukan karena keilmuan yang ditawarkan, melainkan peluang
kerja yang dianggap lebih menjanjikan setelah lulus. Padahal, belajar suatu
bidang ilmu sejatinya bertujuan untuk memahami ilmu tersebut secara mendalam,
serta memberi kontribusi nyata bagi masyarakat.
“Jadi, siapa
yang diuntungkan? Para industrialis, para pebisnis. Itu yang diuntungkan,”
tuturnya.
Dalam
pemaparannya, Gus Dhofir mengaitkan kondisi tersebut dengan peran Sumitro
Djojohadikusumo saat menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia pada masa awal pemerintahan Presiden Soeharto. Kala itu, Sumitro
mengirim ratusan mahasiswa indonesia untuk menempuh pendidikan ekonomi di
University of California, Berkeley, Amerika Serikat.
Para alumni
yang kemudian dikenal sebagai “Mafia Berkeley” tersebut mendapat peran
strategis dalam merancang kebijakan ekonomi nasional. Selain di sektor ekonomi,
pengaruh mereka juga merambah ke dunia pendidikan melalui penyebaran paradigma
ekonomi yang berorientasi pada kebutuhan dunia kerja.
Lebih jauh, Gus
Dhofir menjelaskan bahwa embrio sistem pendidikan di Indonesia bermula pada
masa kolonial Belanda. Pada abad ke-19, pemerintah kolonial mulai mendirikan
sekolah melalui kebijakan politik etis setelah memperoleh keuntungan besar dari
eksploitasi ekonomi di Hindia Belanda.
“Kok tidak ada
sekolah, kok hanya pabrik isinya, lalu dibikin sekolah. Itu disebut dengan
politik balas budi atau politik etis,” jelasnya.
Meski demikian,
Gus Dhofir menyayangkan bahwa hingga kini Indonesia belum sepenuhnya mampu
merancang sistem pendidikan yang benar-benar mandiri. Sistem yang diterapkan
tidak jauh berbeda dengan warisan kolonial, termasuk penyeragaman kurikulum dan
metode pembelajaran di berbagai daerah.
“Setiap wilayah
memiliki karakter sosial dan kebutuhan yang berbeda. Ada masyarakat pesisir,
daratan, perkebunan, hingga persawahan, yang tentu memerlukan pendekatan
pendidikan yang tidak seragam. Lalu mengapa justru meniru Belanda?,”
pungkasnya.
